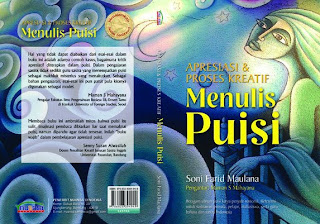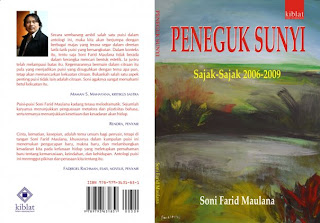Pemetik Bintang
Minggu, 16 September 2012
Khazanah l Pikiran Rakyat l 9 September 2012
Sajak-sajak Soni Farid Maulana
Pindang Ikan
Pindang ikan mas tersedia di atas meja makan, di sebuah rumah makan pinggir kota, Di layar kaca seorang pelantun dangdut meliukkan tubuhnya dengan pakaian serba mini, dengan ukuran bh 36 a. “Tidak itu 38 b,” kata yang lain. Dan kau memalingkan muka. “Lagu ini sungguh menyebalkan,” katamu. Ingatan masa silam sebusuk bangkai anjingkah, yang membuat dirimu berkata demikian? Aku tidak tahu.
Sungguh aku hanya diam, dipukau tubuh pelantun dangdut, tak peduli dengan ukuran bh yang dipakainya. Goyang pinggulnya lebih dahsyat dari tsunami Aceh, sanggup merubuhkan dinding imanku hingga hancur berantakan di ruang dalam. Sekali lagi aku hanya diam seperti pindang ikan emas yang siap disantap, saat kau berkata, “aku butuh hawa segar di luar sana. Selera makanku hilang!”
Hhmm, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku bawa sepiring nasi dan pindang ikan mas ke luar ruangan? Sedang hasratku yang paling purba menghardik diriku untuk tetap duduk di tempat, dan mataku tidak mau lepas dari liukan tubuh pelantun dangdut di layar kaca, yang mengingatkan diriku pada liukan tubuhmu pada sebuah malam di sebuah kamar di Puncak.
Nun di luar sana, aku melihat dirimu muntah-muntah. Seketika itu pula mata batinku melihat tujuh ekor gagak hitam melayang terbang di atas kepalamu. Aku pucat, aku gemetar dibuatnya. Maut yang bengis membayang dalam benakku. Dalam benakku. “Apa yang terjadi dengan dirimu, dengan isi perutmu?” batinku. Sebuah dialog dari sebuah film picisan melintas dalam kepalaku, “aku belum siap jadi bapak!” kata sang jantan. “Bajingan!” jawab sang betina. Langit kelabu.
2010
Pulang Kampung
Aku rindu kampung halaman. Ingin pulang ke sana. Arah mana yang harus aku tuju? Mata batinku silau sudah oleh warna-warni kehidupan kota besar. Telingaku tidak lagi bisa menangkap wirid rerumputan sebab selalu dibuai oleh nyanyian dara tujuh belas tahun, yang membuat aku mabuk dan tersungkur di ranjang Dewi Durga segelap palung syahwatnya. Sungguh aku rindu kampung halaman, yang bila gelap malam tiba, aku dengar suara anak-anak mendaras Alquran di surau pinggir kolam. Dalam hening aku dengar suara air pancuran atau suara serangga malam yang semua itu adalah dzikir alam, menghasut hatiku pulang; merindu kampung halaman. Di sini di dalam kamar hotel bintang lima, aku ditemani sebotol minuman ringan juga acara televisi yang membosankan. Sesekali aku terima telepon atau sms dari pacar gelapku, yang entah ada di mana. Hmm, apa yang terjadi dengan semua ini? Malaikat bersayap tujuh atau sembilan kadang aku impikan datang; menjemput diriku pulang ke kampung halaman, yang dirindukan para nabi dan orang suci. Tapi aku, sungguh bukan orang suci. Aku serupa anjing kudisan, yang mengais-ngais sampah di sebuah tempat yang jauh. Ah. Rindu itu sungguh menghasut hatiku, membawa aku pulang kepadaMu. Kau yang bebas dari kehancuran
2010
Cirebon Dini Hari
- untuk Ahmad Syubbanuddin Alwy
Ditikam brandal motor: -- jerit si korban mengguncang dinding kotamu di bawah gelap bulan abad durjana. Adakah ia pahlawan, menikam orang tanpa alasan, lagi tak melawan? Tidak, ia hanya kadal, demikian kau bilang, serupa begundal sundal.
Semacam suluh neraka yang bahan bakunya: batu menyala, setan, dan manusia. O, nun di dunia gelap bawah sana, ia kehilangan suara. Ia ingin menyeru Cahaya Maha Cahaya. Tapi yang diingatnya hanya amis darah, dan jerit si korban di simpang lima.
Betapa ia serupa mawar yang kelopak demi kelopoknya gugur ke tanah sebelum ligar, sebelum salam menilam salam. Dan aku serupa ia dalam kisah yang lain, melolong di kegelapan, disumpal daging busuk Kuntilanak. “Carilah sumber cahaya dalam gelap, sebagaimana Umar ra menemukannya,” kau bilang suatu malam.
Kering angin laut menyapu wajahku. “Tãhã”
2010
Jumat, 14 September 2012
Majalah Sastra Horison l September 2012
Sajak-sajak Soni Farid Maulana
Miqat
Dua lembar kain ihram di tubuhku, seperti pakaian si mati di hari pengadilan, yang berjalan gontai dengan muka tertunduk lesu, tak berani menatap wajahMu, Yang Maha Hakim. Dua lembar kain ihram di tubuhku menjelma linggis gaib, menjebol tangki airmataku di gelap malam, lebih hitam dan bahkan lebih busuk dari air comberan.
Para peziarah berjalan khusyu. “Aku datang kepadaMu, aku penuhi panggilanMu!” Ya Allah, berapa jarak lagi dari Bir Ali langkah kakiku menuju tanah suciMu, mencapai denyut nadi ampunanMu? Betapa ombak laut cahayaMu, aku rindu menenggelamkan adaku dalam nikmat karuniaMu yang kekal.
Di langit Timur Jauh, aku melihat bintang jatuh, juga melihat bayang-bayang diriku yang roboh ditimpa ribuan berhala, ingin meloloskan diri dari kepungan segala suara, yang semua itu bukan suaraMu, bukan firmanMu. Nyata sudah airmataku, malam ini, mengalir deras ke sungguh muara dalam seah talbiyah. Wahai Tuhan para malaikat dan ruh, bakar aku dalam api ampunanMu yang paling mawar.
2010
Jabal Rahmah
Di Jabal Rahmah di Padang Arafah ada kisah Adam-Hawa dipertemukan Tuhan, setelah keduanya berpisah diusir dari sorga. Keduanya dipertemukan Tuhan dalam naungan cintaNya yang kekal, setelah rahmat dan ampunanNya melimpah ke hati keduanya. Dalam putaran waktu, ada tangki air mataku bedah di situ. Lihat, betapa hitam dan busuk airmataku, lebih butek dari air comberan. Sungguh jiwaku merindu ampunanNya, ingin meloloskan diri dari segala kepungan berhala dan kepungan segala suara yang bukan suaraNya. Dalam seah talbiyah menjelangi Hari Arafah nyata sudah adaku bagai kendi pecah. “Ya Allah, hancurkan aku, bentuk kembali aku dalam naungan cintaMu dan ampunanMu yang kekal. Jauhkan aku dari segala suara yang bisa menjatuhkan martabat Adam-Hawa dari sorgaMu!”
2010
Hari Arafah
Inilah hari yang dirindukan itu, hari Arafah. Pintu-pintu langit dan ampunanNya dibukaNya dengan segala keagunganNya. “KaruniaMu ya Allah yang hamba mohon dariMu, dari kemuliaan kasih sayangMu!” begitu suara hatiku aku dengar dalam hening. Siang itu, cahaya matahari bagai mata tombak yang menyala, menusuk ubun-ubunku. Kain ihram basah sudah, tubuhku bau amis bagai ribuan bangkai ikan yang perlahan membusuk dalam hatiku. Tidak. Adaku di situ bagai sebutir pasir yang ditimpa tahi onta di situ. Aku meledak dalam duka. Yang bicara hanya airmata: ketika segala dusta juga segala dosa menampakan dirinya serupa bajingan tengik yang lapar dan liar memperkosa gadis belia di gelap malam, yang setelah itu dihabisi nyawanya, diteguk darahnya. Aku meraung dalam luka. “Sungguh inilah Hari Arafah hari yang dirindukan itu. Aku datang kepadaMu dengan segala adaku sebusuk najis. Aku datang kepadaMu dengan segala damba dan rindu para nabi. Giring aku ke dalam barisan orang-orang yang Kau cintai sepanjang waktu; jangan tendang aku ke dalam jurang yang hina, Wahai Tuhan para malaikat dan ruh!”
2010
Lontar Jumrah
Melewati terowongan Mina, hatiku bergetar diterjang gelombang takbir, tasbih, dan tahmid, juga seah talbiyah; yang mengiringi setiap langkah kaki hambaMu menuju Jumratul-Uula, Wustha, dan ‘Aqabah. Aku berjalan menuju medan perang yang sesungguhnya, melawan diriku sendiri tawanan nafsu kegelapan yang garang dan buas. Dengan menyebut namaMu dan demi keagunganMu, Ya Allah aku lontar jumrah dengan kerikil yang aku pungut di gelap malam di Muzdalifah yang lengang, di bawah terang cahaya bulan. Aku lontar jumrah dengan sesungguh hati, seperti melempar batu ke arah diriku sendiri: Iblis yang mahir menyaru jadi orang suci, peneguk nafsu duniawi, pelayar tangguh gelombang syahwat ribuan peri metropolitan. Sungguh airmataku tak terbendung: -- bedah dan bedah lagi di situ, saat dengan jelas melihat diriku sendiri begitu buruk rupa luar-dalam, malu sungguh berdiri di hadapanMu Yang Maha Suci. Ya Allah, di tengah-tengah lautan orang suci, aku bersyukur bisa menghirup angin rahmatMu seharum mawar negeri langit; yang berhembus ke arah makhlukMu, ketika cahaya pagi merekah, dan langit di atas kepala jernih sudah.
2010
Batu Nisan
Magrib belum tiba memang, tapi cahaya di luar sana remang sudah. Seremang itukah cahaya di parasmu, mendaras mataku. Bila laut berdebur seperti suara yang bangkit dari alam kubur, saat itulah, bintang berekor dari arah timur jauh menyeret ingatanku akan dirimu, yang dulu pernah berkata, aku mencintaimu. Tapi apa artinya dulu dan kini -- bila dalam gelap -- kilau matamu masih menyimpan getar, semacam debar, dan burung-burung Attar kembali terbang menyusur alur takbir, alun dzikir. Kekasihku, antara batu nisan, aksara purba dan lumut hijau di sela akar pohonan; maut yang cerlang menungguku di situ, seiring gelombang doa sapu jagat diucap para jamaah di rumahNya yang purba, bergetar hingga ke langit jauh, hingga ribuan berhala runtuh dalam hatiku.
2011
SONI FARID MAULANA lahir 19 Februari 1962 di Tasikmalaya, Jawa Barat, dari pasangan Yuyu Yuhana bin H. Sulaeman dan R. Teti Solihati binti Didi Sukardi. Masa kecil dan remaja, termasuk pendidikannya, mulai tingkat SD, SMP, dan SMA ditempuh di kota kelahirannya. Tahun 1985, Soni menyelesaikan kuliah di Jurusan Teater, Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI) sekarang Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung. Aktif menulis puisi sejak tahun 1976, dipublikasikan di berbagai media massa cetak terbitan daerah dan ibukota. Sejumlah puisi yang ditulisnya sudah dibukukan dalam sejumlah antologi puisi tunggal, antara lain dalam Tepi Waktu Tepi Salju (Kelir, 2004) Variasi Parijs van Java (PT. Kiblat Buku Utama, 2004), Secangkir Teh (PT. Grasindo, 2005), Sehampar Kabut (Ultimus, 2006), Angsana (Ultimus, 2007), Opera Malam (PT. Kiblat Buku Utama, 2008), Pemetik Bintang (PT Kiblat Buku Utama, 2008), Peneguk Sunyi (PT Kiblat Buku Utama, 2009), Mengukir Sisa Hujan (Ultimus, 2010) dan Disekap Hujan (Kelir, 2011).
Selain itu, dimuat juga dalam antologi puisi bersama seperti Tonggak IV (PT Gramedia, 1987), Winternachten (Stichting de Winternachten, Den Haag, 1999), Angkatan 2000 (PT. Gramedia, 2001), Dari Fansuri Ke Handayani (Horison, 2001), Gelak Esai & Ombak Sajak Anno 2001 (Penerbit Buku Kompas, 2001) Hijau Kelon & Puisi 2002 (Penerbit Buku Kompas, 2002) Horison Sastra Indonesia (Horison, 2002), Puisi Tak Pernah Pergi Penerbit Buku Kompas, 2003) Nafas Gunung (Dewan Kesenian Jakarta, 2004), Living Together (Kalam, 2005), Antologia de Poéticas (PT Gramedia, 2009), Danau Angsa (PT. Gramedia, 2011), Equator (Yayasan Cempaka Kencana, 2011), Bangga Aku Jadi Rakyat Indonesia (Kosa Kata Kita, 2011), Kitab Radja-Ratoe Alit (Kosa Kata Kita, 2011) dan sejumlah antologi puisi lainnya.
Dua kumpulan puisi yang ditulisnya, Sehampar Kabut dan Angsana meraih Hadiah Sastra Lima Besar Khatulistiwa Literary Award untuk periode 2005-2006, dan 2006-2007. Sebelumnya sebuah puisi yang ditulisnya dalam bahasa Sunda, Sajak Tina Sapatu Jeung Baju Sakola Barudak meraih Hadiah Sastra LBSS (1999). Sedangkan sebuah esai yang ditulisnya Taufiq Ismail Penyair Yang Peka Terhadap Sejarah meraih Anugerah Jurnalistik Zulharmans dari PWI Pusat, Jakarta (1999). Selain itu, Soni berkali-kali mendapat Hadiah Puisi Juniarso Ridwan lewat puisi Sunda yang ditulis dan dipublikasikannya di majalah Sunda, Manglé. Pada bulan Desember 2010 mendapat Anugerah Budaya 2010 dari Gubernur Jawa Barat untuk bidang penulisan karya sastra.
Selain menulis puisi dalam bahasa Indonesia, Soni menulis puisi dalam bahasa Sunda, dipublikasikan di Tabloid SundaGalura, Majalah Sunda Mangle, dan Cupu Manik. Sejumlah puisi Sunda yang ditulisnya dibukukan dalam antologi puisi tunggal, Kalakay Méga (Cetakan 3, 2007, CV Geger Sunten). Selain itu dimuat juga dalam antologi puisi bersama, antara lain dalam antologi puisi Saratus Sajak Sunda (CV Geger Sunten 1992), Sajak Sunda Indonesia Emas (CV. Geger Sunten, 1995) dan Antologi Puisi Sajak Sunda (PT. Kiblat Buku Utama, 2007). Selanjutnya, selain menulis puisi, Soni menulis pula sejumlah esai, dan cerita pendek. Esainya tentang puisi dibukukan Selintas Pintas Puisi Indonesia (Jilid 1, PT. Grafindo, 2004, dan Jilid 2, 2007). Sedangkan sejumlah cerita pendek yang ditulisnya antara lain dibukukan dalam Orang Malam (Q-Press, 2005) dan Empat Dayang Sumbi (Komunitas Sastra Lingkar Selatan) dan Fiksi Mini (Kosa Kata Kita, 2011). Di samping itu, namanya dicatat Ajip Rosidi dalam entri Enslikopedi Budaya Sunda (PT. Pustaka Jaya, 2000) dan Apa Siapa Orang Sunda (Kiblat Buku Utama, 2003).
Sebagai penyair, Soni, berkali-kali diundang oleh Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) untuk membacakan sejumlah puisi yang ditulisnya di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta antara lain dalam forum Puisi Indonesia 1987, dan Cakrawala Sastra Indonesia 2005. Pada tahun 1990 mengikuti South East Asian Writers Conference di Queezon City, Filipina. Pada 1999 mengikuti Festival de Winternachten di Den Haag, Belanda. Pada 2002 mengikuti Festival Puisi Internasional Indonesia di Bandung, dan International Literary Biennale Living Together 2005 di Bandung, dan sejumlah acara sastra lainnya.***
Minggu, 27 Mei 2012
Buku Baru Soni Farid Maulana
Judul: Apresiasi dan Proses Kreatif Menulis Puisi
Penulis: Soni Farid Maulana
Pengantar: Maman S Mahayana
Penerbit: Nuansa Cendekia, Juni 2012
Tebal: 198 Hlm
ISBN: 978-602-8394-94-9
Harga: Rp 38.000
Beberapa Petikan Isi Buku:
DORONGAN hati menulis puisi, muncul dalam diri seorang penyair tidak datang begitu saja dari dunia tak dikenal, akan tetapi datang dari sebuah pengalaman, yang dihayatinya secara total. Pengalaman yang dimaksud ada kalanya disebut sebagai pengalaman puitik, yang sumbernya bisa berasal dari pengalaman fisik maupun dari pengalaman metafisik dalam pengertian yang seluas-luasnya.
Dalam mengungkap pengalamannya itu, seorang penyair bisa mengungkap hubungan dirinya dengan Tuhan, dengan sesama manusia, maupun dengan alam yang mengitarinya. Ketika pengalaman tersebut hendak diekspresikan dalam bentuk tulisan, maka hati dan pikiran seorang penyair dengan segera memilih sejumlah kosa kata dari sebuah bahasa yang dikuasainya dengan baik. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa yang selama ini digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Entah itu bahasa Sunda, Indonesia, Inggris, Jerman, Perancis, Cina, Arab, dan bahasa-bahasa lainnya yang tumbuh dan berkembang di muka bumi.
Dalam mengekspresikan pengalaman batinnya itu ke dalam bentuk tulisan, tentu saja seorang penyair membutuhkan imajinasi, simbol, dan metafor sebagai kendaraan utamanya. Dan apa yang disebut dengan imajinasi sebagaimana dikatakan Yasraf Amir Piliang adalah mekanisme psikis dalam melihat, melukiskan, membayangkan, atau memvisualkan sesuatu di dalam struktur kesadaran, yang menghasilan sebuah citra (image) pada otak.
Kemampuan dalam membayangkan dan memvisualkan sesuatu itulah yang ditulis oleh seorang penyair dalam sebuah puisi, yang bahan dasarnya dikreasi dari sebuah pengalaman puitik yang dihayatinya secara total. Almarhum Rendra menyebutnya sebagai pengalaman batin yang telah dihancur leburkan terlebih dahulu, untuk kemudian dibentuk kembali menjadi dunia baru, dunia yang sama sekali beda dengan kenyataan hidup sehari-hari. Semua itu divisualkan lewat kata-kata yang telah dipilih oleh sang penyair secara sungguh-sungguh dalam sebuah puisi yang ditulisnya.....(Puisi, Dorongan Hati, dan Realitas Maya, halaman 21-22)
DALAM kehidupan manusia dewasa ini, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk mentransformasikan pikiran, gagasan, maupun perasaan-perasan estetik dalam sebuah teks, baik berupa karya sastra, esai, maupun teks lainnya, yang di dalamnya mengandung citra, majas, metafor, dan simbol. Adapun yang disebut teks dalam kaitan tersebut merupakan teks yang bertalian maknanya, dalam hal ini teks puisi.
Dalam konteks tersebut, jelas sudah, bahwa imajinasi mempunyai peran yang cukup penting dalam merealisasikan gagasan, ide, maupun perasaan estetik yang ditulis dalam karya sastra maupun teks-teks lainnya dengan tujuan agar si pembaca (penerima pesan) bisa memahami, menangkap dengan cepat akan isi pikiran, gagasan, maupun perasaan-perasaan estetik yang dipancarkan oleh teks yang tengah dibacanya itu dengan penuh gairah. Berkaitan dengan itu, secara umum yang disebut dengan imajinasi adalah daya untuk membentuk gambaran atau konsep mental yang secara langsung atau tidak langsung didapatkan dari sensansi pengindaraan, yang semua itu terekam dengan jelas dalam otak.
Sekali lagi, dengan tegas tadi disebutkan bahwa yang disebut dengan imajinasi adalah daya untuk membentuk gambaran. Lantas apa itu gambaran? Yang dimaksud dengan gambaran dalam tulisan ini adalah sesuatu yang tengah terjadi dan dibayangkan bentuknya dalam kepala untuk kemudian dikonkretkan dan divisualkan dengan media kata-kata. Salah satu sarana untuk memvisualkan apa yang tengah kita bayangkan itu, antara lain lewat bahasa figuratif.
Daya membentuk gambaran itulah pokok soal dalam imajinasi. Oleh karena itu proses mengimajinasikan sesuatu selalu merupakan proses membentuk gambaran tertentu, dan itu terjadi secara mental, yang didalamnya melibatkan persoalan-persoalan psikologis agar si pengirim dan penerima imajinasi bisa sejajar dalam gelombang yang sama sehingga transformasi ide, gagasan, perasaan-perasaan estetik bisa terkomunikasikan dengan baik.
Di dalam puisi, apa yang disebut dengan gaya bahasa, ungkapan, atau ungkara dalam bahasa Sunda, sering juga disebut semantik, yang posisinya ditulis dalam sebuah sintaksis, yang merujuk pada sebuah makna kata, bagian kalimat, atau pada kalimat itu sendiri. Secara umum semua itu disebut majas. Dan apa yang disebut majas, sebagaimana dikatakan Jan van Luxemburg, Mieke Bal, dan Willem G. Weststeijn, secara garis besar dibagi dalam tiga bagian, yakni majas pertentangan, majas identitas atau majas analogi (bahasa figuratif), dan majas kedekatan.,.(Kerja Majas Dalam Puisidan Iklan, Halaman 43-44)
Dalam percakapannya dengan penulis di rumah Herry Dim pada tahun 2006 lalu, Rendra mengatakan puisi Pertemuan Malam lahir ketika ia dalam keadaan sakit, yang antara sadar dan tidak sadar, dirinya melayang ke sebuah alam, yang disebutnya sebuah hutan. Di sana ia bertemu dengan orang-orang yang dicintainya, sebagaimana diungkap di atas. Pengalaman itu, kental dengan persoalan spiritual, dimana cinta tidak musnah disebabkan oleh kematian, meski yang satu hidup di alam yang ini dan yang lainnya hidup di alam sana.
“Puisi adalah penghayatan dari pengalaman. Karena itu, ia tidak bisa ditulis berdasar pada khayalan semata-mata seakan-akan kita mengalami peristiwa itu. Secara esensial lewat puisi tersebut saya ingin mengungkapkan pengalaman spiritual saya, bahwa kebutuhan manusia akan cinta nyata adanya. Cinta yang hakiki, yang bisa membuat manusia bahagia adalah cinta karena Allah, yang Insya Allah atas semua itu, Allah SWT akan membalasNya dengan rahmat dan karuniaNya yang melimpah ke dalam hati manusia, yang mencintai sesamanya dengan tulis ikhlas, karena Allah,” ujar Rendra. Ia tidak hanya dikenal sebagai penyair, tetapi juga sebagai teaterawan terkemuka di negeri ini, dengan sejumlah naskah drama yang ditulisnya. Puisi tersebut secara lengkap kita baca di bawah ini:... (Rendra, "Puisi Lahir dari Pengalaman yang Dihayati, Halaman 67-68)
Buku ini terdapat 14 esai yang isinya fokus pada apresiasi karya puisi para penyair ternama. Di antara karya penyair tersebut adalah. Amir Hamzah, Chairil Anwar, Ws Rendra, Remy Sylado, Wing Kardjo, Saiki KM, Arifin C Noor, Acep Zamzam Noor, Oka Rusmini, Sinta Ridwan, Dorothea Rosa Herliany dan masih banyak lagi.
Sebagai seorang penyair dan wartawan, Soni Farid Maulana memiliki pandangan yang luas disertai kemampuan menulis esai yang berpijak kaidah jurnalistik. Setiap esai mengupas karya para penyair secara simple namun akurat. Simpel artinya berdasarkan pemilihan objek-objek karya yang layak diapresiasi dengan mengedepankan akurasi penilaian. Itulah mengapa buku ini sangat cocok untuk kelompok pembaca seperti sastrawan pemula, pelajar, mahasiswa, serta guru-guru bahasa dan sastra Indonesia.
Melalui buku ini, pembaca, selain diajarkan untuk menilai karya puisi, juga memiliki nilai manfaat praktis sebagai panduan berkarya. Soni memberikan panduan yang tepat untuk pembaca untuk sebuah proses kreatif menulis puisi. Sebuah buku yang memperkaya khasanah kesusastraan nasional dan karena ini sangat baik dijadikan modul pembelajaran ruang sekolah.(Penerbit Buku Nuansa Cendekia)***
Bagi yang berminat membeli buku ini bisa inbox (facebook) Rak Buku Soni atau langsung menghubungi Penerbit buku Nuansa Cendekia, Jln. Sukub Baru No. 23, Ujungberung, Bandung 40619. E-mail: nuansa.cendekia@gmail.com
Penulis: Soni Farid Maulana
Pengantar: Maman S Mahayana
Penerbit: Nuansa Cendekia, Juni 2012
Tebal: 198 Hlm
ISBN: 978-602-8394-94-9
Harga: Rp 38.000
Beberapa Petikan Isi Buku:
DORONGAN hati menulis puisi, muncul dalam diri seorang penyair tidak datang begitu saja dari dunia tak dikenal, akan tetapi datang dari sebuah pengalaman, yang dihayatinya secara total. Pengalaman yang dimaksud ada kalanya disebut sebagai pengalaman puitik, yang sumbernya bisa berasal dari pengalaman fisik maupun dari pengalaman metafisik dalam pengertian yang seluas-luasnya.
Dalam mengungkap pengalamannya itu, seorang penyair bisa mengungkap hubungan dirinya dengan Tuhan, dengan sesama manusia, maupun dengan alam yang mengitarinya. Ketika pengalaman tersebut hendak diekspresikan dalam bentuk tulisan, maka hati dan pikiran seorang penyair dengan segera memilih sejumlah kosa kata dari sebuah bahasa yang dikuasainya dengan baik. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa yang selama ini digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Entah itu bahasa Sunda, Indonesia, Inggris, Jerman, Perancis, Cina, Arab, dan bahasa-bahasa lainnya yang tumbuh dan berkembang di muka bumi.
Dalam mengekspresikan pengalaman batinnya itu ke dalam bentuk tulisan, tentu saja seorang penyair membutuhkan imajinasi, simbol, dan metafor sebagai kendaraan utamanya. Dan apa yang disebut dengan imajinasi sebagaimana dikatakan Yasraf Amir Piliang adalah mekanisme psikis dalam melihat, melukiskan, membayangkan, atau memvisualkan sesuatu di dalam struktur kesadaran, yang menghasilan sebuah citra (image) pada otak.
Kemampuan dalam membayangkan dan memvisualkan sesuatu itulah yang ditulis oleh seorang penyair dalam sebuah puisi, yang bahan dasarnya dikreasi dari sebuah pengalaman puitik yang dihayatinya secara total. Almarhum Rendra menyebutnya sebagai pengalaman batin yang telah dihancur leburkan terlebih dahulu, untuk kemudian dibentuk kembali menjadi dunia baru, dunia yang sama sekali beda dengan kenyataan hidup sehari-hari. Semua itu divisualkan lewat kata-kata yang telah dipilih oleh sang penyair secara sungguh-sungguh dalam sebuah puisi yang ditulisnya.....(Puisi, Dorongan Hati, dan Realitas Maya, halaman 21-22)
DALAM kehidupan manusia dewasa ini, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk mentransformasikan pikiran, gagasan, maupun perasaan-perasan estetik dalam sebuah teks, baik berupa karya sastra, esai, maupun teks lainnya, yang di dalamnya mengandung citra, majas, metafor, dan simbol. Adapun yang disebut teks dalam kaitan tersebut merupakan teks yang bertalian maknanya, dalam hal ini teks puisi.
Dalam konteks tersebut, jelas sudah, bahwa imajinasi mempunyai peran yang cukup penting dalam merealisasikan gagasan, ide, maupun perasaan estetik yang ditulis dalam karya sastra maupun teks-teks lainnya dengan tujuan agar si pembaca (penerima pesan) bisa memahami, menangkap dengan cepat akan isi pikiran, gagasan, maupun perasaan-perasaan estetik yang dipancarkan oleh teks yang tengah dibacanya itu dengan penuh gairah. Berkaitan dengan itu, secara umum yang disebut dengan imajinasi adalah daya untuk membentuk gambaran atau konsep mental yang secara langsung atau tidak langsung didapatkan dari sensansi pengindaraan, yang semua itu terekam dengan jelas dalam otak.
Sekali lagi, dengan tegas tadi disebutkan bahwa yang disebut dengan imajinasi adalah daya untuk membentuk gambaran. Lantas apa itu gambaran? Yang dimaksud dengan gambaran dalam tulisan ini adalah sesuatu yang tengah terjadi dan dibayangkan bentuknya dalam kepala untuk kemudian dikonkretkan dan divisualkan dengan media kata-kata. Salah satu sarana untuk memvisualkan apa yang tengah kita bayangkan itu, antara lain lewat bahasa figuratif.
Daya membentuk gambaran itulah pokok soal dalam imajinasi. Oleh karena itu proses mengimajinasikan sesuatu selalu merupakan proses membentuk gambaran tertentu, dan itu terjadi secara mental, yang didalamnya melibatkan persoalan-persoalan psikologis agar si pengirim dan penerima imajinasi bisa sejajar dalam gelombang yang sama sehingga transformasi ide, gagasan, perasaan-perasaan estetik bisa terkomunikasikan dengan baik.
Di dalam puisi, apa yang disebut dengan gaya bahasa, ungkapan, atau ungkara dalam bahasa Sunda, sering juga disebut semantik, yang posisinya ditulis dalam sebuah sintaksis, yang merujuk pada sebuah makna kata, bagian kalimat, atau pada kalimat itu sendiri. Secara umum semua itu disebut majas. Dan apa yang disebut majas, sebagaimana dikatakan Jan van Luxemburg, Mieke Bal, dan Willem G. Weststeijn, secara garis besar dibagi dalam tiga bagian, yakni majas pertentangan, majas identitas atau majas analogi (bahasa figuratif), dan majas kedekatan.,.(Kerja Majas Dalam Puisidan Iklan, Halaman 43-44)
Dalam percakapannya dengan penulis di rumah Herry Dim pada tahun 2006 lalu, Rendra mengatakan puisi Pertemuan Malam lahir ketika ia dalam keadaan sakit, yang antara sadar dan tidak sadar, dirinya melayang ke sebuah alam, yang disebutnya sebuah hutan. Di sana ia bertemu dengan orang-orang yang dicintainya, sebagaimana diungkap di atas. Pengalaman itu, kental dengan persoalan spiritual, dimana cinta tidak musnah disebabkan oleh kematian, meski yang satu hidup di alam yang ini dan yang lainnya hidup di alam sana.
“Puisi adalah penghayatan dari pengalaman. Karena itu, ia tidak bisa ditulis berdasar pada khayalan semata-mata seakan-akan kita mengalami peristiwa itu. Secara esensial lewat puisi tersebut saya ingin mengungkapkan pengalaman spiritual saya, bahwa kebutuhan manusia akan cinta nyata adanya. Cinta yang hakiki, yang bisa membuat manusia bahagia adalah cinta karena Allah, yang Insya Allah atas semua itu, Allah SWT akan membalasNya dengan rahmat dan karuniaNya yang melimpah ke dalam hati manusia, yang mencintai sesamanya dengan tulis ikhlas, karena Allah,” ujar Rendra. Ia tidak hanya dikenal sebagai penyair, tetapi juga sebagai teaterawan terkemuka di negeri ini, dengan sejumlah naskah drama yang ditulisnya. Puisi tersebut secara lengkap kita baca di bawah ini:... (Rendra, "Puisi Lahir dari Pengalaman yang Dihayati, Halaman 67-68)
Buku ini terdapat 14 esai yang isinya fokus pada apresiasi karya puisi para penyair ternama. Di antara karya penyair tersebut adalah. Amir Hamzah, Chairil Anwar, Ws Rendra, Remy Sylado, Wing Kardjo, Saiki KM, Arifin C Noor, Acep Zamzam Noor, Oka Rusmini, Sinta Ridwan, Dorothea Rosa Herliany dan masih banyak lagi.
Sebagai seorang penyair dan wartawan, Soni Farid Maulana memiliki pandangan yang luas disertai kemampuan menulis esai yang berpijak kaidah jurnalistik. Setiap esai mengupas karya para penyair secara simple namun akurat. Simpel artinya berdasarkan pemilihan objek-objek karya yang layak diapresiasi dengan mengedepankan akurasi penilaian. Itulah mengapa buku ini sangat cocok untuk kelompok pembaca seperti sastrawan pemula, pelajar, mahasiswa, serta guru-guru bahasa dan sastra Indonesia.
Melalui buku ini, pembaca, selain diajarkan untuk menilai karya puisi, juga memiliki nilai manfaat praktis sebagai panduan berkarya. Soni memberikan panduan yang tepat untuk pembaca untuk sebuah proses kreatif menulis puisi. Sebuah buku yang memperkaya khasanah kesusastraan nasional dan karena ini sangat baik dijadikan modul pembelajaran ruang sekolah.(Penerbit Buku Nuansa Cendekia)***
Bagi yang berminat membeli buku ini bisa inbox (facebook) Rak Buku Soni atau langsung menghubungi Penerbit buku Nuansa Cendekia, Jln. Sukub Baru No. 23, Ujungberung, Bandung 40619. E-mail: nuansa.cendekia@gmail.com
Senin, 25 April 2011
Rabu, 15 September 2010
Puisi dari Kenangan yang Terus Membayang
 Catatan Kecil SONI FARID MAULANA
Catatan Kecil SONI FARID MAULANA SETIAP orang punya narasi, yang bersumber pada pengalaman, pada kenangan yang terus membayang. Tentu saja narasi yang dimaksud bukan narasi yang selama ini diperbincangkan oleh para filsuf dan pemikir kebudayaan pada umumnya. Narasi yang dimaksud adalah narasi yang personal sifatnya, yang menggoda pikiran dan hati sang penyair untuk mengekalkannya dalam baris-baris puisi yang ditulisnya, yang boleh jadi tidak seluruhnya berhasilnya disimpan dan dikekalkannya dalam lemari kata-kata. Di dalam kehidupan, manusia senantiasa berhadapan dengan ironi-ironi, yang disadari atau tidak menjadi sumber penciptaan bagi puisi-puisi yang ditulisnya.
Di satu sisi, ia sadar bahwa dirinya fana, takut dikejar-kejar kematian di kala senang. Namun di pihak lainnya, ia begitu mengharapkan kematian datang menjemput dirinya – ketika situasi kejiwaannya tengah goncang, dilanda putus cinta, atau ditampar oleh sebuah pengalaman buruk yang tidak bisa ditanggungnya secara nyata. Dalam kondisi semacam itu, beberapa puisi yang saya tulis lahir dari pengalaman yang kelam, seperti di bawah ini:
DI ATAS PANGGUNG
Shakespeare mengapa kau tulis kisah Romeo
dan Julia? Racun cinta yang aku teguk berbenih
maut dalam dadaku. Sedang hujan yang turun
sejak pagi tak mengubah apa-apa.
duka Romeo yang mengendap dalam kalbuku
mengekalkan keasinganku akan martabat dan derajat
akan status dan kehormatan yang bila
gelap malam tiba menikam pungguku dari belakang
atas semua itu Shakespeare dengar nyanyianku
yang satu ini. Bahwa cinta tak selamanya mampu
menjelaskan cahaya bulan yang terbit di hati
bahwa kelelawar tak mampu menghirup cahaya
matahari, yang diburunya berabad-abad
saat terjaga, hanya kursi, kecoa, dan kain hitam
di atas panggung. Sedang lampu-lampu redup sudah
sedang hatiku bagai hamparan padang rumput
yang bergemuruh menahan kengerian hidup
yang dingin dan sunyi dipeluk embun dini hari
lalu angin dingin berhembus lagi ke ruang ini
ke panggung ini, ke lantai kayu ini,
ke tubuhku ini. Ke tubuhku ini
1985
Setelah sekian jarak saya menulisnya, saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Donny Gahral Adian dalam pengantarnya untuk buku Yasraf Amir Piliang, yang saya pinjam dalam tulisan ini, untuk menjelaskan apa dan bagaimana proses kreatif itu mempunyai hubungan yang erat dengan realitas kehidupan, yang menjelma narasi yang mempribadi itu.
Donny bilang, kesadaran tentang kefanaan berbanding lurus dengan kesadaran akan kesejatian. Manusia yang menyejarah adalah satu-satunya sosok yang sangat terganggu dengan kefanaan itu. Sebuah ironi menarik. Sosok yang sadar akan kefanaan sekaligus, adalah ia yang gandrung akan kesejatian.
Hidup memang ada dalam kondisi yang demikian. Sudah sewajarnya, dalam mengasah dirinya, seorang penyair harus pula peka terhadap hal-hal semacam itu. Dan bila hal itu dihayati secara sungguh-sungguh, maka ia akan serupa dengan sumber pencerahan. Setidaknya setelah jatuh dalam gelap, saya merasa lebih dewasa lagi dalam sebuah pengalaman spiritual yang lebih luas dan dalam, dari apa yang saya alami sebelumnya.
Semua itu tentu saja bertitik pangkal pada realitas kehidupan, dan itu artinya, bukan berangkat dari sesuatu yang dibayangkan, yang bersumber dari ruang yang kosong, dari hati dan pikiran yang tidak mengalami apa-apa. Selain puisi di atas, saya menulis pula puisi lainnya, yang bersumber dari pengalaman semacam yang nyaris sama, dengan situasi dan variasinya yang lain lagi, seperti di bawah ini:
BINTANG MATI
duduk di bangku kayu, menghayati
sorot matamu yang kelam oleh kabut dukacita
aku temukan bintang mati
bintang yang dulu berpijar dalam langit jiwaku
aku temukan kembali -- begitu hitam dan gosong
dan kau menjerit terpisah dari cintaku.
dengarkan aku bicara, suaraku
bagai ketenangan air sungai bagai keheningan
batu-batu dasar kali melepas bau segar tumbuhan.
bila hari kembang;
suaraku membangun kehidupan yang porak-poranda
oleh gempa peradaban. Ya, kutahu kota yang gemerlap
menyesatkan rohanimu dari jalanku.
hanya ini yang bisa kuberikan kepadamu:
rasa gula terperas dari tebu jiwaku. Reguklah,
biar jiwamu berkilau kembali. O, bintang
yang dulu benderang dalam langit jiwaku.
1987-1989
Tentu saja, bukan hanya persoalan cinta, dan hati yang luka, yang menjadi sumber penciptaan puisi bagi seorang penyair. Ada banyak sumber lainnya yang menyebabkan hati kita tergerak, dan terpanggil untuk menulisnya. Penyair dengan demikian bukan hanya berdiri sebagai saksi zaman, ia juga bertindak sebagai juru tulis dan bahkan jurus tafsir bagi penggalan-penggalan riwayat hidupnya, atau riwayat masyarakat dan negaranya, yang dikekalkannya dalam setiap lapisan kata-kata, yang di satu sisi boleh jadi menyusup ke dalam balik kulit lapisan bunyi vokal dan konsonan yang menjelma lambang, symbol, apapun namanya.
Dalam konteks semacam inilah, saya yakini bahwa di dalam karya seni yang demikian senantiasa ada kegiatan jiwa yang terus-menerus hadir, bolak-balik, mondar-mandiri antara kenangan dan realitas hidup yang dihadapinya secara nyata. Pendeknya, reaksi terhadap rangsangan yang menggairahkan mungkin bisa diterangkan hubungan sebab akibatnya; tapi kegiatan kreatif, yang merupakan antithesis atau lawan yang mutlak dari apa yang dibayang-bayangkan saja, jelas tidak akan membuat sebuah karya seni terasa ruhnya, karena ia kehilangan akar, kehilangan konteks yang menjadi sumber acuan dalam berproses kreatif.
Itu sebabnya saya sering mendapat pertanyaan, “saya sering buntu dalam menulis puisi, kata-kata seakan hilang dari ingatan?” Tanya Siti Mirantini dalam sebuah acara diskusi puisi, tempo hari di Banjarmasin dalam acara Sastrawan Bicara Siswa Bertanya (SBSB) yang diselenggarakan oleh majalah sastra Horison bekerjasama dengan Ford Foundation. Jika kita mengenal dengan baik seluruh sudut dan ruang dari pengalaman, atau kenangan yang terus membayang dalam ingatan kita, insya Allah, kita tidak akan pernah kehilangan kata-kata, karena kata-kata datang dengan sendirinya. “Kata-kata seakan memburu kita, meminta kita untuk melahirkannya jadi sebuah puisi,” ujar penyair Sutardji Calzoum Bachri dalam sebuah kesempatan di Universitas Lidah Buaya, Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, sebelum terbang ke Banjarmasin.
Setidaknya, demikianlah selintas kilas saya hendak mengatakan akan pentingnya mengenali pengalaman, yang tidak pernah lepas dari realitas kehidupan, walau benar ketika ia menjelma symbol, hal-hal yang bersifat artistik dan estetik, dan sebagainya, dan sebagainya, sudah menjadi dunia yang lain, yang isi dan maknanya hanya akan bisa diungkap bila kita mampu menafsirnya. Peka terhadap pengalaman, lebih tepatnya lagi peka terhadap suasana yang melingkari pengalaman tersebut, adalah ruh dari puisi, yang tidak hanya bersumber pada daya intelektual saja. Paling tidak, saya memahami proses kreatif penulisan puisi, dari sisi semacam ini salah satu sisinya.
Lepas dari persoalan tersebut di atas apa yang dinamakan kenangan dalam konteks yang demikian itu adalah pengalaman juga. Ia selain berurusan dengan persoalan-persoalan hati yang luka, bisa juga berupa sebuah tempat yang tidak bisa lupakan. Tempat itu bisa di dalam atau di luar negeri. Dan apa yang berkait dengan tempat, bisa juga merupakan penggambaran dari tempat itu, atau dari sebuah peristiwa batin yang berkait dengan tempat itu. Fokus terhadap satu bagian dari tempat dan peristiwa yang terjadi pada sebuah tempat di mana kita berarada, itulah yang dinamakan sudut penciptaan puisi, yang tentu berbeda dengan apa yang disebut dengan sudut pandang. Dan apa yang dinamakan sudut pandang biasanya lebih kepada penentuan nilai-nilai, sedangkan apa yang dinamakan sudut penciptaan puisi lebih mengarah pada kejelian kita dalam menangkap dan mengkristalkan peristiwa puitik yang menghampiri kita secara telanjang bulat, merangsang, dan menggairahkan. Satu dari sekian puisi yang saya tulis berkait dengan tempat adalah seperti puisi di bawah ini:
PARIS LA NUIT
dua jam yang lalu
di Brasserie Lipp sambil minum anggur
aku tunggu Charles Baudelaire,
ia tak kunjung datang dari negeri kelam.
omongan balau, asap rokok,
juga sebaris imaji yang liar melintas di situ.
malam beranjak tua mengenakan mantelnya
yang hitam bergaris angin musim dingin.
sepanjang Saint-Germain
lampu menyala. Kata dan lagu asing
menyerbu pendengaranku.
cahaya bulan dan bintang disapu kabut.
langkah kakiku terasa penat, naik-turun
undakan nilai-nilai berduri maut.
sebab hidup mengalir ke hilir
sebab bahagia dan derita tipis batasnya
sekali lagi dalam hawa yang dingin
aku teguk anggur merah.
perlahan dan sangat perlahan di hadapan
gerbang dunia tak di kenal membuka
cahayanya lebih sunyi dari ribuan lampu
yang menyala sepanjang Saint-Germain
manusia lalu di sana, seperti katamu,
menyeberangi hutan lambang
1999
Puisi tersebut saya tulis di tempat tinggal penyair Sitor Situmorang di Paris, setelah pada malam hari sebelumnya, saya, penyair Rendra, Nenden Lilis Aisyah, Ken Zuraida, Agus R. Sardjono, Jeff Paimin dan seorang perempuan yang saya lupa namanya mengajak menikmati Kota Paris malam hari di kawasan Saint-Germain, yang indah. Brasserie Lipp yang ada di kawasan tersebut serupa dengan restoran mewah, tempat aktor dan aktris film yang bermukim di Kota Paris makan di situ. Konon tempat itu pernah pula didatangi oleh para filsuf di kota tersebut. Pikiran saya pada malam itu tiba-tiba saja ingat Charles Baudelaire, salah seorang tokoh puisi modern Prancis dengan gerakan puisi surealisme yang menghebohkan pada zamannya (1821-1867).
Dalam kondisi yang demikian itu batin saya berhadapan dengan yang nyata dan tidak nyata. Semua bercampur-aduk, menjelma pengalaman yang mistis, dan bahkan magis. Untuk itu benarlah apa yang dikatakan Rendra, pengalaman puitik adalah pengalaman yang tidak diduga kedatangannya. Bila ia menyapa batin kita jangan ditolak, biarkan ia masuk ke relung hati terdalam, hingga tumbuh, besar dan matang. Pada waktunya ia akan seperti bayi, tanpa diminta akan lahir sendiri.
Ketika puisi lahir dengan sendirinya, ternyata secara otomatis apa yang dinamakan majas dalam tataran semantik maupun sintaksis lahir pula dengan sendirinya. Jadi sebuah pengalaman yang matang pada kenyataannya telah menyiapkan segalanya. Jika pun terjadi revisi, hanya revisi kecil, mencari kata yang sepadan untuk kepentingan rima, atau untuk pendalaman makna agar apa yang ingin diekspresikan itu tepat adanya, dan kita pun menjadi puas karenanya.***
Selasa, 14 September 2010
Majalah Sastra Horison, September 2009
Sajak-sajak Soni Farid Maulana
PULANG
- untuk Heni Hendrayani
rumah yang aku tuju sudah terlihat
bayang-bayangnya. Tujuh lapis tirai kabut terangkat
di hadapan. Siapakah yang menungguku di rumah itu?
cahaya kegelapan atau cahaya rohanikah yang kelak
menyambut ruhku di ruang tamu?
bahwa hidup yang aku tempuh ke muka
tidak mulus, memang. Ada kalanya kakiku
tersandung batu, serupa mawar hitam yang tumbuh
di belukar liar. Di situ maut sungguh bengis,
pandang matanya sungguh api. Tubuhku hangus
dalam waktu yang sia-sia.
jika aku pulang di malam lengang, di hatiku
tersimpan sebuah ruang yang telah aku sucikan
untukmu, hanya untukmu semata. Aku mengerti
bila kau tak ingin masuk ke dalamnya,
sebab kau tidak ingin menyingkirkan yang lain.
tidak apa.
sekali lagi, jalan pulang sudah terbentang.
ada rumput ilalang yang basah oleh hujan. Cintaku,
jangan teteskan airmatamu di jalan itu. Biarkan
hanya basah hujan, dan sisa kabut yang mengendap
di palung daging daun-daun. Dan kini, lepas aku
dengan hatimu yang tulus, sebagaimana aku
mencintaimu bukan untuk nafsu
2009
BAYANG-BAYANG
siapa yang memarkir kereta jenazah
sewarna pucuk rangasu di halaman tubuhku?
yang punya rumah belum lagi berbenah,
walau cahaya matahari condong ke arah petang.
sungguh, jalan pulang memang sudah tampak
di hadapan, dan rumah yang dituju
memang sudah terlihat bayang-bayangnya.
jika aku bilang bahwa dalam hatiku ada ruang
yang telah aku sucikan untukmu, maka siapa lagi
yang aku tunggu selain dirimu? Betapa cinta kita
berdesis bagai ular hitam di rumpun malam. Di antara
yang nyata dan yang maya. Berdesis tidak untuk
cari korban.
kemarilah cintaku, sejenak saja. Lihat kereta
jenazah yang di parkir sang waktu di halaman tubuhku
sudah seharum kembang mayang. Dan pak kusir
sudah duduk di takhta kesayangannya, siap tarik tali kekang,
siap menuju alamat, ke sebuah tempat yang mungkin
tidak sempat kita ingat. Kita? Tidak, bukan kita
yang akan berangkat, tapi aku.
sekali lagi, kemarilah cintaku. Buka ruang yang telah
aku sucikan untukmu. Masuklah. Ada setangkai bakung
merah, yang aku petik dari taman kesunyianku sehabis bulan
dilepas mega malam. Ada juga selapis kain putih,
yang dulu aku pakai ketika tawaf di baitullah. Semua itu,
untukmu. Untuk menyeka dukamu.
2009
REMANG MIANG
sungguh aku begitu sunyi ketika kau
tak menjawab smsku, meski maut yang aku tunggu.
apa yang membuat hatimu menutup pintu
hingga segala ruang percakapan
menjadi sunyi serupa tugu batu? Kemarin malam
kita masih bercakap tentang rembulan yang luka
ditusuk runcing pucuk pinus.
kau bilang sore ini kau harus pulang.
ya, aku mengerti, dan kita memang akan pulang.
tapi kau pulang ke mana, ke Batavia? Aku sendiri
pulang ke tempat yang lain, di mana
Yang Maha Kekal: --tegak -- sudah di hadapan,
lalu bau kesturi. Lelebihnya bau bunga bangkai.
o maut, kawan akrab negeri kelam.
cintaku, dengarkan aku bicara,
sungguh kau telah meruang-mewaktu
dalam batinku. Tapi mengapa kau masih juga ragu,
bahkan tidak percaya kepadaku? Apakah aku
serupa drakula di hadapanmu? Jika serupa itu,
mengapa jendela hatimu masih kau biarkan
terbuka ke arahku, hingga kilau lampu
di kamarmu berkedip: serupa morse,
-- isyarat rindumu kepadaku? -- O, maut,
kawan akrab mimpi hitam.
2009
KELAM
lalu siapa yang berkelebat dalam ruang
yang telah aku sucikan untukmu,
kalau bukan dirimu? Koak burung gagak
dalam kelam. Ledakan bintang merah di langit hitam.
o maut sahabat karib negeri gaib.
sekali lagi, siapa yang berkelebat dalam ruang
yang telah aku sucikan untukmu, kalau bukan dirimu?
ya, memang, aku mendengar langkah itu. Lebih halus
dari derai kabut di pucuk pohonan. Lebih lembut
dari jejak gerimis di kelopak bunga angsana. O maut
karib malang dalam duka.
sekali lagi aku bertanya, mengapa kau, cintaku,
tak juga datang ke tempat ini, ke ruang ini, ruang
yang telah aku sucikan untukmu? Betapa jarak
dan bahasa telah memisah kita. O maut
: -- salib ruhku di tulang rusuknya –
hingga segala makna: lebur dalam tiada,
ke titik asal hidupku bermula.
2009
AMBANG PETANG
malam bergulir di tangkai daun
serupa sisa hujan ambang petang
lebih lembut dari embun airmataku
yang tumpah di sisi kiri baitullah –
dan maut begitu nyata di pangkuanku
sekali lagi, di sisi kiri baitullah
airmataku tumpah. Langit begitu jernih
disepuh cahaya bulan. Kalbuku
pedih sungguh dirajam pisau kegelapan
senyata maut yang rebah di pangkuanku
o, jalan pulang yang terbentang
di hadapan. O, ruang yang telah aku sucikan
untukmu, sunyi sungguh, serupa batu hitam
di dasar sumur tua. Dan kini, kuntum harap
tak lagi mekar serupa ligar mawar
di belukar liar, sejak kau serupa bayang-
bayang di kelir batinku.
2009
TERATAI
ada teratai biru mekar di kedalaman.
teratai ini teratai hatiku, untukmu. Ia
lebih biru dari inti api yang bukan api.
seandainya kau melihatnya malam hari,
ketika cahaya bulan menyentuh miring:
-- kau akan berkata, “semekar itukah
rindumu kepadaku?” Ya. Segairah itu pula:
-- ajal, sang mempelai, menantiku
di ranjang waktu.
teratai ini, teratai yang lain, cintaku. Ia
lebih wangi dari kembang kabung,
lebih bersinar dari cahaya matahari,
lebih redup dari kilau matamu, ketika perlahan
terpejam di sisiku. Dalam pelukanku. O, maut
datang dan pergi bagai dentang jam.
2009
MELATI AIR
ini melati air untukmu, cintaku. Melati ini,
tidak wangi, memang. Tapi warnanya
yang putih, dan wujudnya yang sederhana itu
adalah sebuah puisi. Aku suka melati ini:
dalam gelap aku bertanya, apa artinya
wangi dan tidak wangi, bila ia begitu cepat sirna
dalam hidup kita?
bukankah yang abadi, cintaku,
bukan soal wangi dan tidak wangi
dalam hidup kita? Yang abadi
adalah seberapa sungguh kita mengada,
tumbuh dalam dunia yang kita damba.
lalu, hidup itu apa? Betapa batas dan tepi,
terhampar di hadapan. O, maut
getar layar gaib perahu waktu.
cintaku, ada malam-malam panjang
dalam hidupku tanpa cahaya bulan, tanpa
bunyi musik. Tanpa derai angin di ranting
pepohonan. Ada kesunyian biru senyap
membungkus ruhku di sudut waktu
dan, kau, cintaku, serupa dewi asri, terbang
ke pusat cahaya yang tak tercatat alam raya,
alam gaib dalam getar jantungku
2009
BAKUNG
bukankah cahaya lilin di atas meja
tinggal sehembusan napas lagi, cintaku?
cahaya remang di sela rimbun dedaunan
menggarisbawahi bayang-bayang detik jam
yang menilam lumpur di atas kubur.
apa yang kau ragukan, cintaku?
ruang yang aku sucikan untukmu sudah seharum
kembang bakung. Sudah seharum bunga setaman:
-- harum bunga -- yang bukan sembarang bunga
dalam hidupku, aku sunting untukmu.
o maut, yang berkelebat dalam derai hujan,
menjaring angin dingin di ranting pohonan,
yang berdesir dan berdesir searus alir air.
sedang di sini, di ruang ini, hanya cahaya lilin,
remang malam, dan kau tak ada
di sampingku.
2009
Selain dimuat dimajalah sastra Horison,juga dimuat dalam kumpulan puisi Peneguk Sunyi (Kiblat Buku Utama, 2009)
PULANG
- untuk Heni Hendrayani
rumah yang aku tuju sudah terlihat
bayang-bayangnya. Tujuh lapis tirai kabut terangkat
di hadapan. Siapakah yang menungguku di rumah itu?
cahaya kegelapan atau cahaya rohanikah yang kelak
menyambut ruhku di ruang tamu?
bahwa hidup yang aku tempuh ke muka
tidak mulus, memang. Ada kalanya kakiku
tersandung batu, serupa mawar hitam yang tumbuh
di belukar liar. Di situ maut sungguh bengis,
pandang matanya sungguh api. Tubuhku hangus
dalam waktu yang sia-sia.
jika aku pulang di malam lengang, di hatiku
tersimpan sebuah ruang yang telah aku sucikan
untukmu, hanya untukmu semata. Aku mengerti
bila kau tak ingin masuk ke dalamnya,
sebab kau tidak ingin menyingkirkan yang lain.
tidak apa.
sekali lagi, jalan pulang sudah terbentang.
ada rumput ilalang yang basah oleh hujan. Cintaku,
jangan teteskan airmatamu di jalan itu. Biarkan
hanya basah hujan, dan sisa kabut yang mengendap
di palung daging daun-daun. Dan kini, lepas aku
dengan hatimu yang tulus, sebagaimana aku
mencintaimu bukan untuk nafsu
2009
BAYANG-BAYANG
siapa yang memarkir kereta jenazah
sewarna pucuk rangasu di halaman tubuhku?
yang punya rumah belum lagi berbenah,
walau cahaya matahari condong ke arah petang.
sungguh, jalan pulang memang sudah tampak
di hadapan, dan rumah yang dituju
memang sudah terlihat bayang-bayangnya.
jika aku bilang bahwa dalam hatiku ada ruang
yang telah aku sucikan untukmu, maka siapa lagi
yang aku tunggu selain dirimu? Betapa cinta kita
berdesis bagai ular hitam di rumpun malam. Di antara
yang nyata dan yang maya. Berdesis tidak untuk
cari korban.
kemarilah cintaku, sejenak saja. Lihat kereta
jenazah yang di parkir sang waktu di halaman tubuhku
sudah seharum kembang mayang. Dan pak kusir
sudah duduk di takhta kesayangannya, siap tarik tali kekang,
siap menuju alamat, ke sebuah tempat yang mungkin
tidak sempat kita ingat. Kita? Tidak, bukan kita
yang akan berangkat, tapi aku.
sekali lagi, kemarilah cintaku. Buka ruang yang telah
aku sucikan untukmu. Masuklah. Ada setangkai bakung
merah, yang aku petik dari taman kesunyianku sehabis bulan
dilepas mega malam. Ada juga selapis kain putih,
yang dulu aku pakai ketika tawaf di baitullah. Semua itu,
untukmu. Untuk menyeka dukamu.
2009
REMANG MIANG
sungguh aku begitu sunyi ketika kau
tak menjawab smsku, meski maut yang aku tunggu.
apa yang membuat hatimu menutup pintu
hingga segala ruang percakapan
menjadi sunyi serupa tugu batu? Kemarin malam
kita masih bercakap tentang rembulan yang luka
ditusuk runcing pucuk pinus.
kau bilang sore ini kau harus pulang.
ya, aku mengerti, dan kita memang akan pulang.
tapi kau pulang ke mana, ke Batavia? Aku sendiri
pulang ke tempat yang lain, di mana
Yang Maha Kekal: --tegak -- sudah di hadapan,
lalu bau kesturi. Lelebihnya bau bunga bangkai.
o maut, kawan akrab negeri kelam.
cintaku, dengarkan aku bicara,
sungguh kau telah meruang-mewaktu
dalam batinku. Tapi mengapa kau masih juga ragu,
bahkan tidak percaya kepadaku? Apakah aku
serupa drakula di hadapanmu? Jika serupa itu,
mengapa jendela hatimu masih kau biarkan
terbuka ke arahku, hingga kilau lampu
di kamarmu berkedip: serupa morse,
-- isyarat rindumu kepadaku? -- O, maut,
kawan akrab mimpi hitam.
2009
KELAM
lalu siapa yang berkelebat dalam ruang
yang telah aku sucikan untukmu,
kalau bukan dirimu? Koak burung gagak
dalam kelam. Ledakan bintang merah di langit hitam.
o maut sahabat karib negeri gaib.
sekali lagi, siapa yang berkelebat dalam ruang
yang telah aku sucikan untukmu, kalau bukan dirimu?
ya, memang, aku mendengar langkah itu. Lebih halus
dari derai kabut di pucuk pohonan. Lebih lembut
dari jejak gerimis di kelopak bunga angsana. O maut
karib malang dalam duka.
sekali lagi aku bertanya, mengapa kau, cintaku,
tak juga datang ke tempat ini, ke ruang ini, ruang
yang telah aku sucikan untukmu? Betapa jarak
dan bahasa telah memisah kita. O maut
: -- salib ruhku di tulang rusuknya –
hingga segala makna: lebur dalam tiada,
ke titik asal hidupku bermula.
2009
AMBANG PETANG
malam bergulir di tangkai daun
serupa sisa hujan ambang petang
lebih lembut dari embun airmataku
yang tumpah di sisi kiri baitullah –
dan maut begitu nyata di pangkuanku
sekali lagi, di sisi kiri baitullah
airmataku tumpah. Langit begitu jernih
disepuh cahaya bulan. Kalbuku
pedih sungguh dirajam pisau kegelapan
senyata maut yang rebah di pangkuanku
o, jalan pulang yang terbentang
di hadapan. O, ruang yang telah aku sucikan
untukmu, sunyi sungguh, serupa batu hitam
di dasar sumur tua. Dan kini, kuntum harap
tak lagi mekar serupa ligar mawar
di belukar liar, sejak kau serupa bayang-
bayang di kelir batinku.
2009
TERATAI
ada teratai biru mekar di kedalaman.
teratai ini teratai hatiku, untukmu. Ia
lebih biru dari inti api yang bukan api.
seandainya kau melihatnya malam hari,
ketika cahaya bulan menyentuh miring:
-- kau akan berkata, “semekar itukah
rindumu kepadaku?” Ya. Segairah itu pula:
-- ajal, sang mempelai, menantiku
di ranjang waktu.
teratai ini, teratai yang lain, cintaku. Ia
lebih wangi dari kembang kabung,
lebih bersinar dari cahaya matahari,
lebih redup dari kilau matamu, ketika perlahan
terpejam di sisiku. Dalam pelukanku. O, maut
datang dan pergi bagai dentang jam.
2009
MELATI AIR
ini melati air untukmu, cintaku. Melati ini,
tidak wangi, memang. Tapi warnanya
yang putih, dan wujudnya yang sederhana itu
adalah sebuah puisi. Aku suka melati ini:
dalam gelap aku bertanya, apa artinya
wangi dan tidak wangi, bila ia begitu cepat sirna
dalam hidup kita?
bukankah yang abadi, cintaku,
bukan soal wangi dan tidak wangi
dalam hidup kita? Yang abadi
adalah seberapa sungguh kita mengada,
tumbuh dalam dunia yang kita damba.
lalu, hidup itu apa? Betapa batas dan tepi,
terhampar di hadapan. O, maut
getar layar gaib perahu waktu.
cintaku, ada malam-malam panjang
dalam hidupku tanpa cahaya bulan, tanpa
bunyi musik. Tanpa derai angin di ranting
pepohonan. Ada kesunyian biru senyap
membungkus ruhku di sudut waktu
dan, kau, cintaku, serupa dewi asri, terbang
ke pusat cahaya yang tak tercatat alam raya,
alam gaib dalam getar jantungku
2009
BAKUNG
bukankah cahaya lilin di atas meja
tinggal sehembusan napas lagi, cintaku?
cahaya remang di sela rimbun dedaunan
menggarisbawahi bayang-bayang detik jam
yang menilam lumpur di atas kubur.
apa yang kau ragukan, cintaku?
ruang yang aku sucikan untukmu sudah seharum
kembang bakung. Sudah seharum bunga setaman:
-- harum bunga -- yang bukan sembarang bunga
dalam hidupku, aku sunting untukmu.
o maut, yang berkelebat dalam derai hujan,
menjaring angin dingin di ranting pohonan,
yang berdesir dan berdesir searus alir air.
sedang di sini, di ruang ini, hanya cahaya lilin,
remang malam, dan kau tak ada
di sampingku.
2009
Selain dimuat dimajalah sastra Horison,juga dimuat dalam kumpulan puisi Peneguk Sunyi (Kiblat Buku Utama, 2009)
Tajug Rencana HU Pikiran Rakyat, 8 September 2010
Soni Farid Maulana
Idul Fitri
fajar 1 syawal di ufuk timur
fajar yang basah oleh takbir dan tahmid.
adakah cahaya idul fitri
terbit lebih cerah dari cahaya matahari
dalam langit kalbuku sehitam arang?
di lapangan terbuka
sajadah demi sajadah umur
terhampar ke arah kiblat
basah oleh airmata
yang pedih ditinggal bulan puasa
bulan yang penuh rahmat
dan ampunan Allah ‘Azza Wajalla.
“wahai manusia
batas umur adalah kubur
adakah bulan puasa tahun ini
bukan hanya haus dan lapar
bagi kita yang menjalaninya
dengan penuh rasa syukur?”
suara itu jelas terdengar
ketika angin lembut pagi hari
menyisir rerumputan
takbir dan tahmid pun bergema
menggungcang ruang dalam
ruang dadaku yang kelam.
“wahai manusia
mengapa kau masih juga sibuk
dengan urusan keduniawian,
mengapa kau hardik fakir miskin
dari halaman rumahmu,
yang justru dengan itu
sesungguhnya ia tengah bekerja
memperindah puasamu. Sayang,
kau telah mengancurkannya
dengan kata-kata kasarmu!”
suara itu kembali terdengar
sesaat sebelum rakaat salat idul fitri
ditegakkan di atas sajadah umur
yang tidak hanya terhampar ke arah kiblat
tetapi juga menukik ke arah kubur
ke tepi waktu ke tepi salju. Dan aku,
tak kuasa berdiri tegak, betapa keropos
isi dadaku. “Amal macam apakah
yang aku jalanani selama ini, kotor
dan berdebu: di bulan puasa
yang mungkin tidak lagi aku jumpa
di tahun depan. Di tahun depan?”
sesaat hening menilam hening
alun takbir dan tahmid terdengar nyaring
dalam pengupinganku yang dalam
yang membangkitkan seluruh ingatanku
sehitam aspal jalanan. Cahaya alif,
betapa aku rindu selamanya
terpancar dari segenap rahmat
dan ampunan Allah ‘Azza Wajalla
melimpahi kalbuku, kalbu
umat Muhammad saw
di hari idul fitri
2010
Idul Fitri
fajar 1 syawal di ufuk timur
fajar yang basah oleh takbir dan tahmid.
adakah cahaya idul fitri
terbit lebih cerah dari cahaya matahari
dalam langit kalbuku sehitam arang?
di lapangan terbuka
sajadah demi sajadah umur
terhampar ke arah kiblat
basah oleh airmata
yang pedih ditinggal bulan puasa
bulan yang penuh rahmat
dan ampunan Allah ‘Azza Wajalla.
“wahai manusia
batas umur adalah kubur
adakah bulan puasa tahun ini
bukan hanya haus dan lapar
bagi kita yang menjalaninya
dengan penuh rasa syukur?”
suara itu jelas terdengar
ketika angin lembut pagi hari
menyisir rerumputan
takbir dan tahmid pun bergema
menggungcang ruang dalam
ruang dadaku yang kelam.
“wahai manusia
mengapa kau masih juga sibuk
dengan urusan keduniawian,
mengapa kau hardik fakir miskin
dari halaman rumahmu,
yang justru dengan itu
sesungguhnya ia tengah bekerja
memperindah puasamu. Sayang,
kau telah mengancurkannya
dengan kata-kata kasarmu!”
suara itu kembali terdengar
sesaat sebelum rakaat salat idul fitri
ditegakkan di atas sajadah umur
yang tidak hanya terhampar ke arah kiblat
tetapi juga menukik ke arah kubur
ke tepi waktu ke tepi salju. Dan aku,
tak kuasa berdiri tegak, betapa keropos
isi dadaku. “Amal macam apakah
yang aku jalanani selama ini, kotor
dan berdebu: di bulan puasa
yang mungkin tidak lagi aku jumpa
di tahun depan. Di tahun depan?”
sesaat hening menilam hening
alun takbir dan tahmid terdengar nyaring
dalam pengupinganku yang dalam
yang membangkitkan seluruh ingatanku
sehitam aspal jalanan. Cahaya alif,
betapa aku rindu selamanya
terpancar dari segenap rahmat
dan ampunan Allah ‘Azza Wajalla
melimpahi kalbuku, kalbu
umat Muhammad saw
di hari idul fitri
2010
Langganan:
Postingan (Atom)